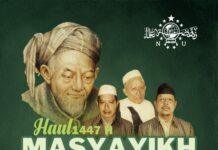Oleh: Ustaz M Syaifuddin SHI MMA
Ramadan selalu menjadi momentum yang dinanti umat Islam di seluruh dunia. Namun di Indonesia, hampir setiap tahunnya, penentuan awal bulan suci ini kerap diwarnai perbedaan, terutama antara pengikut metode hisab (perhitungan astronomi) dan pengikut metode rukyat (pengamatan hilal).
Menjelang Ramadan 1446 H, potensi perbedaan ini kembali menjadi perbincangan. Namun kali ini, yang menjadi perbincangan adalah potensi perbedaan antara hasil hisab taqwimy (perhitungan astronomis yang dipakai untuk pembuatan kalender baik di Kemenag RI, Nahdlatul Ulama maupun Ormas lain) dengan prediksi hasil rukyatul hilal.
Lantas, bagaimana kemungkinan perbedaan tersebut terjadi, dan apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan antara hasil hisab taqwimy dengan prediksi hasil rukyatul hilal?
Perlu diketahui bahwa ijtima’ akhir Syakban terjadi pada Jumu’ah Legi, 28 Februari 2025 M pukul 07:47 WIB/ 08:47 WITA/ 09.47 WIT.
Secara perhitungan astronomis (hisab qoth’i) ketinggian hilal saat Maghrib di seluruh wilayah Indonesia ± 3 sampai 4,7 derajat di atas ufuk dengan elongasi 4,8 sampai 6,4 derajat. Artinya dengan menggunakan kacamata kriteria imkanurrukyah (visibilitas hilal) MABIMS BARU yang mensyaratkan tinggi hilal ≥ 3 derajat dengan elongasi ≥ 6,4 derajat sudah terpenuhi meskipun hanya di wilayah Barat Indonesia tepatnya di daerah Aceh, sedang hampir di semua lokasi di seluruh Indonesia, belum terpenuhi dari sisi elongasi (jarak busur dari titik pusat Bulan ke titik pusat Matahari saat terbenam).
Keputusan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025 M di Kalender Indonesia (Hisab Taqwimy), tentunya, selain berdasar hisab astronomis imkanurrukyah (visibilitas hilal) MABIMS BARU juga didasarkan pada mathla’ wilayatul hukmi, yang dalam konteks Indonesia mempunyai pengertian bahwa batas pemberlakuan keputusan masuknya awal bulan Hijriyah baru yaitu mencakup seluruh kawasan di seluruh Indonesia.
Artinya, meskipun hanya sebagian kecil saja wilayah yang secara hisab sudah memenuhi kriteria imkanurrukyah MABIMS BARU, itu sudah cukup menjadi dasar penentuan awal bulan Hijriyah versi Kalender Indonesia.
Masalahnya, penentuan awal puasa di Indonesia tidak hanya sekadar menggunakan perhitungan astronomis (hisab) saja, akan tetapi tetap memperhatikan serta mempertimbangkan hasil rukyatul hilal pada 29 Syaban 1446 H/ 28 Februari 2025 M, yang kemudian akan di-istbat-kan oleh Pemerintah Indonesia; dalam hal ini oleh Kemenag RI.
Padahal, sebagaimana dilansir Kompas.com saat mewawancarai Deputi Bidang Klimatologi BMKG, disampaikan, bahwa puncak musim hujan di Indonesia pada 2025 ini diprediksi akan berlangsung hingga Februari 2025.
Ini menjadi kekhawatiran, jika pada 28 Februari 2025, saat prosesi rukyatul hilal dilaksanakan khususnya di wilayah Aceh mengalami mendung atau bahkan hujan, sehingga hilal gagal diamati.
Apabila terjadi kondisi seperti ini maka setidaknya ada dua kemungkinan prediksi terkait hasil sidang itsbat itu. Pertama, sesuai hasil rukyatul hilal, Pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Ahad Pon, 2 Maret 2025 dengan dasar istikmal (menggenapkan bulan Syakban 30 hari).
Kedua, bisa jadi Pemerintah akan tetap menetapkan 1 Ramadan 1446 H pada Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 (sesuai kalender) atas dasar hisab dengan mengacu Fatwa MUI Tahun 1981, yang menyatakan bahwa jika perhitungan hisab qath’i menunjukkan adanya hilal setelah terbenam matahari dan semestinya dapat terlihat, namun karena suatu hal tidak dapat dilihat, maka keadaan tersebut cukup dijadikan pedoman untuk menetapkan awal atau akhir Ramadan.
Jika hasil sidang itsbat sesuai kemungkinan yang kedua, tentu tidak mengagetkan. Lantas bagaimana dengan sikap kita apabila 1 Ramadan 1446 H ditetapkan pada Ahad Pon, 2 Maret 2025 M, sesuai kemungkinan pertama?
Tentu sebagai warga Negara yang baik, mestinya patuh terhadap keputusan Pemerintah RI, tanpa harus mendiskreditkan hasil hisab taqwimy (kalender) atau bahkan jadwal imsakiyah yang mungkin oleh sebagian hasib sudah menetapkan mulai 1 Maret 2025 M dalam penulisan jadwal Imsakiyahnya.
Terlebih, mengingat jadwal imsakiyah yang secara esensi adalah serupa dengan jadwal salat harian, dan tidak terpengaruh dengan penetapan awal bulan Hijriyah, maka semestinya persoalan awal dan akhir Ramadan biarlah menjadi persoalan tersendiri yang hasil akhirnya kita serahkan kepada Pemerintah Indonesia sebagai ulil amri.
Sedangkan persoalan jadwal imsakiyah, biarlah tetap fokus di dalam menentukan batasan waktu yang relevan dengan kondisi geografis suatu tempat, khususnya waktu imsak, Shubuh dan Maghrib yang erat kaitannya dengan kapan dimulainya puasa dan kapan saatnya berbuka.
Dari sudut pandang in, tentunya masyarakat diharapkan mampu memahami sehingga tidak ada lagi kata-kata “Jadwal Imsakiyah keliru” lantaran awal puasanya tidak sesuai dengan keputusan Pemerintah RI”. Wallahu a’lam. (*)
Ustaz M Syaifuddin SHI MMA,
Muhadlir Ma’had Aly TBS Kudus dan pengurus Lembaga Falakiyah NU Jawa Tengah.