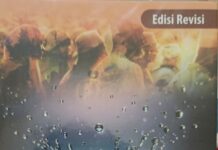Di banyak kampung dan desa-desa, masyarakat masih sangat menggantungkan arah hidupnya pada sosok-sosok yang dianggap memiliki ilmu dan kedudukan spiritual. Seperti ustaz (guru), kiai, dan mursyid thariqah, seringkali mendapat “tempat Istimewa” dalam ruang batin dan sosial masyarakat. Sosok-sosok tersebut senantiasa didengarkan, dihormati, bahkan diikuti tanpa banyak tanya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika figur yang telah ditokohkan itu, ternyata menyimpan cacat moral yang tersembunyi atau bahkan sudah terang-terangan?
Mengusik Nurani
Sudah jamak dan lumrah, bahwa seorang tokoh yang sering berceramah, memimpin jamaah, pemimpin ormas, bahkan mursyid thariqah, akan dikenal oleh Masyarakat luas. Namanya harum. Figurnya dikenal luas. Dan ucapannya seolah menjadi fatwa tak tertulis di masyarakat.
Namun realitas kekinian, kerap kali kita jumpai seorang tokoh atau figur yang perilaku pribadinya, justru tidak sejalan dengan apa yang ia dakwahkan; melakukan tindakan amoral, menyulut kontroversi, dan terlibat dalam dinamika sosial yang menimbulkan keresahan.
Akan tetapi, lantaran masyarakat sudah telanjur menganggapnya sebagai panutan (tokoh yang layak diteladani), sehingga figur tersebut tetap ditokohkan tanpa koreksi yang memadai.
Inilah titik rawan yang jarang disadari: saat masyarakat awam tidak memiliki referensi lain atau terlalu takut untuk mengritisi seorang tokoh, maka pemakluman terhadap penyimpangan pun menjadi norma baru.
Dampaknya, dalam jangka panjang, hal tersebut bisa menyebabkan adanya dekadensi moral kolektif, di mana standard akhlak menjadi kabur, dan nilai kebenaran digantikan oleh kepatuhan semu pada simbol-simbol keagamaan.
Cerdas Memilih Panutan
Menjadi tokoh agama sejati, tidak cukup hanya menguasai teks atau fasih dalam berdakwah. Ia harus menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai yang disampaikannya. Dalam Islam, panutan sejati disebut sebagai uswah hasanah (teladan yang baik).
Allah Subhanahu wa Ta’ala menegaskan dalam Al Quran: “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu…” (QS. Al-Ahzab: 21)
Untuk itu, masyarakat perlu dididik untuk membedakan antara simbol dan substansi, antara gelar dan akhlak, antara sorban dan perbuatan.
Dengan kata lain, bahwa dalam memilih seorang tokoh panutan, masyarakat tidak boleh hanya menilai dari penampilan lahirnya saja, tetapi paling tidak dengan memperhatikan empat hal.
Empat hal tersebut adalah: 1). Akhlak dan integritas pribadi; 2). Konsistensi antara ucapan dan perbuatan; 3). Transparansi dan tanggung jawab sosial; 4). Kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan umat.
Selain itu, pamahaman akan ciri-ciri keulamaan juga perlu dipahami. Antara lain tawadhu’ (rendah hati), yakni tidak mencari popularitas atau kekuasaan; Ikhlas dalam mengajar dan membimbing umat; Menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari fitnah dunia; Tidak menjadikan agama sebagai alat dagang atau alat politik; Konsisten dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah; serta berani berkata benar walaupun pahit.
Imam Al Ghazali menyebutkan, bahwa ulama sejati adalah mereka yang mengutamakan akhirat, tidak menjual fatwa untuk kepentingan duniawi, dan selalu menjaga amanah ilmu.
Selain itu, perlu juga memahami apa yang disebut dengan ulama su’ (ulama yang buruk). Yakni orang-orang yang memiliki ilmu agama, tetapi menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam memperingatkan umatnya terhadap bahaya ulama su’ bahwa: “Yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara.” (HR Ahmad)
Apa ciri-ciri ulama su’? Ciri-cirinya yaitu mengatakan apa yang tidak ia kerjakan; Menggunakan agama untuk mencari pengaruh atau kekayaan; Bersikap otoriter dan antikritik; Suka mengafirkan atau membid’ahkan pihak yang berbeda; Menutupi keburukan diri dengan citra keagamaan; dan melakukan tindakan amoral, namun merasa tidak bersalah.
Ulama su’ jika tidak diingatkan, bisa menjadi perusak nilai-nilai agama dari dalam. Maka masyarakat harus waspada, karena bahaya dan daya rusaknya sangat luar biasa: merusak kepercayaan umat terhadap agama itu sendiri.
Lalu, bagaimana Masyarakat mesti bersikap?
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak boleh tinggal diam. Berikut beberapa sikap yang bisa dilakukan. Pertama, berani menilai dengan cerdas. Menilai tokoh bukanlah bentuk dosa. Justru dalam konteks sosial, umat perlu kritis dan rasional. Penilaian harus berdasar pada akhlak, bukan sekadar penampilan.
Kedua, memberi nasihat secara bijak. Jika memungkinkan, tokoh tersebut diingatkan dengan cara yang baik. Bisa melalui tokoh lain yang disegani, atau melalui pendekatan yang persuasif. Dalam Islam, amar makruf nahi munkar adalah kewajiban bersama, termasuk kepada tokoh agama.
Ketiga, membatasi pengaruh sosialnya. Bila tokoh tersebut menolak berubah dan terus menyesatkan umat, maka masyarakat harus berani membatasi perannya. Tidak harus memusuhi, tapi cukup dengan tidak memberikan panggung, tidak mengikuti ceramahnya, dan tidak menjadikannya rujukan.
Keempat, menghadirkan atau memunculkan tokoh alternatif yang kredibel. Carilah figur baru yang lebih kredibel dan bersih secara moral. Dorong para pemuda santri, kader dakwah, atau tokoh lokal yang amanah untuk mengambil peran. Masyarakat yang sehat harus memberi ruang regenerasi moral.
Kelima, perkuat literasi moral dan keagamaan. Lakukan pengajian, diskusi, dan kajian rutin tentang akhlak dan adab. Semakin luas pemahaman masyarakat, semakin kecil peluang tokoh menyimpang untuk menguasai opini.
Akhirnya, perlu disadari, bahwa tidak semua yang berjubah adalah mulia, dan tidak semua yang berceramah adalah itu sosok yang tulus.
Dalam dunia yang semakin kompleks seperti sekarang, masyarakat tidak bisa lagi bertahan dengan pola pikir “asal tokoh”. Diperlukan ketegasan moral dan kecerdasan sosial untuk menjaga agama tetap suci, dan umat tetap terarah. Wallahu a’lam. (*)
Abd Muhid,
Penulis adalah ketua tim instruktur PC GP Ansor Kabupaten Pati.