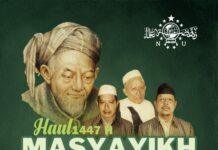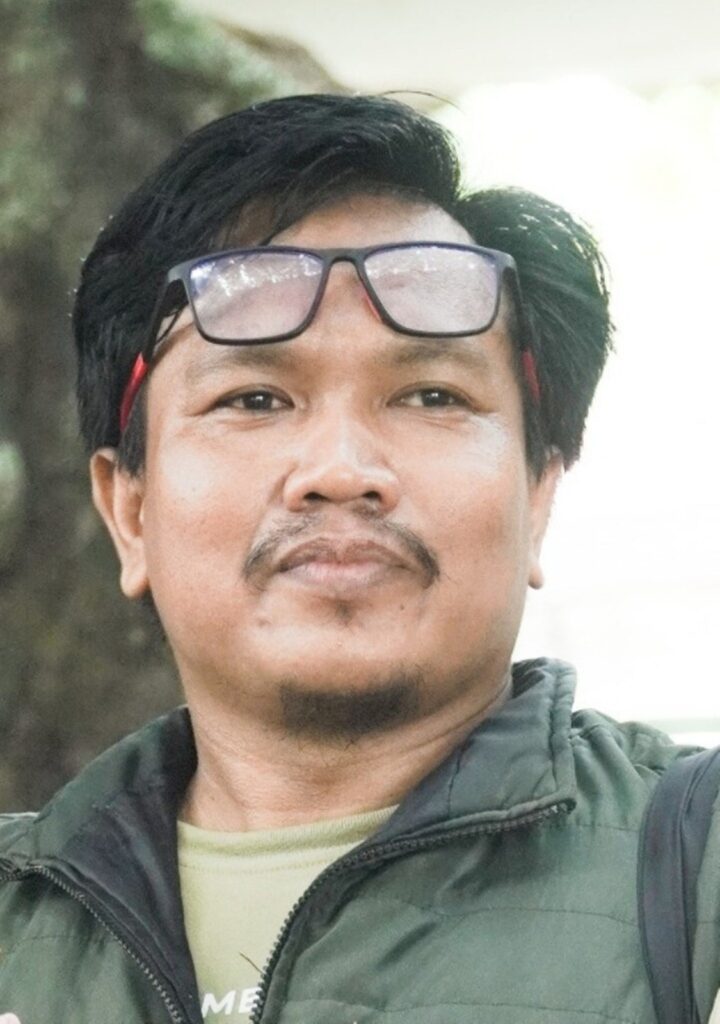Tulisan Dr H Nur Said tentang “Kretek, Pendiri Bangsa, dan Diplomasi Budaya” di Suaranahdliyin.com, membuka kembali ingatan kolektif kita tentang betapa dalamnya akar budaya kretek dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
Dr H Nur Said menyingkap sisi-sisi simbolik yang kerap luput dari pembicaraan publik—bahwa kretek bukan sekadar produk tembakau, melainkan wujud diplomasi kultural yang melekat dalam tubuh bangsa.
Namun, di balik narasi besar tentang Soekarno, KH Hasyim Asy’ari, dan KH Agus Salim, masih banyak kisah lokal yang terlipat di balik kepulan asap: kisah para penggulung, peracik, dan perintis kretek yang memberi nyawa pada simbol-simbol itu sendiri.
Kita sering lupa bahwa sebelum kretek menjadi alat diplomasi di meja perundingan atau simbol kebangsaan di tangan para tokoh besar, ia lebih dulu tumbuh dari tangan-tangan rakyat Kudus, Pati, dan Temanggung—para peracik yang memadukan cengkih dan tembakau dengan doa dan keberanian.
Nama Mbah Djamhari memang disebut sebagai penemu kretek, tetapi sejarah ini juga mencatat nama-nama lain seperti Nitisemito, Atmowidjojo atau M Atmo, Ashadie, Sirin, Sukaenah, Nadiroen, Roesdi, Moeslich, dan Ma’roef.
Dan yang kini masih bertahan antara lain Koo Djie Siang (Nojorono), Oei Gwan (Djarum), dan Mc Wartono (Sukun). Bahkan masih banyak lagi keluarga industri rumahan di Kudus, yang dari dapur-dapur mereka muncul aroma khas yang kelak dikenal dunia.
Mereka bukan diplomat, tetapi tanpa mereka, simbol diplomasi itu tak akan pernah ada.
Tulisan Nur Said seharusnya bisa menembus lapisan ini: bahwa diplomasi budaya tidak hanya terjadi di ruang diplomatik, tetapi juga di ruang produksi—di mana perempuan-perempuan penggulung di pabrik kretek menjadi duta budaya yang tak pernah disebut.
Pada setiap lintingan yang mereka buat, bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga pernyataan eksistensi: bahwa Indonesia punya rasa, punya aroma, dan punya cara sendiri memandang dunia.
Kretek bukan sekadar alat diplomasi karena ia sudah menjadi bentuk cultural resilience—ketahanan budaya yang menyatukan kerja, kepercayaan, dan cita rasa.
Kini, saat kretek kerap direduksi hanya sebagai komoditas industri atau isu kesehatan global, kita perlu mengembalikannya ke akar sejarahnya yang lebih utuh: ia adalah kisah tentang manusia Indonesia yang menemukan jati dirinya lewat asap dan cengkih.
Maka, tulisan seperti yang disampaikan Nur Said menjadi penting untuk dilanjutkan—diperluas dengan menyebut kembali nama-nama kecil yang menjaga bara itu tetap hidup.
Sebab, diplomasi sejati bukan hanya milik para pendiri bangsa, tetapi juga milik mereka yang dari bilik-bilik sederhana Kudus dan sekitarnya telah lama mendiplomasikan aroma Indonesia ke seluruh dunia.
Ma’roef: Santri Pengusaha Kretek
Salah satu kisah yang sering luput dari narasi besar kretek adalah kisah Ma’roef, pendiri Kretek Djambu Bol, yang sejak masa kolonial hingga 1970-an menghidupi ribuan orang di Kudus.
Dalam sejarah kretek, nama Ma’roef menempati posisi unik: ia bukan bangsawan, bukan pejabat, dan bukan pula diplomat -melainkan seorang santri yang menjadi pengusaha, sesuatu yang pada zamannya amat langka.
Kebanyakan santri di awal abad ke-20 lebih akrab dengan dunia mengajar dan berdakwah, sementara berdagang atau berusaha dalam skala besar masih dipandang sebagai wilayah kaum priyayi atau pedagang Tionghoa.
Karena itu, keberhasilan Ma’roef mendirikan dan mengembangkan pabrik Djambu Bol menjadi salah satu kisah penting tentang etika kerja santri yang menemukan bentuknya dalam dunia usaha.
Dari masa kolonial, masa Jepang, hingga awal kemerdekaan, Kretek Ma’roef Cap Djambu Bol terus menguatkan posisinya di pasar Jawa. Baru pada 1950-an, Djambu Bol mulai menembus pasar Sumatra, terutama Lampung. Ketika pengusaha lain kesulitan bertahan pada masa-masa transisi politik, Ma’roef justru sudah memiliki truk operasional sendiri—tanda awal kemapanan usahanya.
Pasar di Lampung memperluas jangkauan Djambu Bol, hingga pada puncaknya perusahaan ini mempekerjakan sekitar 4.000 orang, dengan sebagian besar merupakan pekerja borong tetap. Angka itu menunjukkan bukan hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga daya hidup sosial dari usaha yang lahir dari nilai-nilai pesantren: kerja keras, kesederhanaan, dan kebermanfaatan bagi sesama.
Tradisi Santri dalam Dunia Usaha
Ma’roef bukan pengusaha biasa. Ia tumbuh dari tradisi pesantren yang membentuk karakternya: rendah hati, tekun, dan dekat dengan kiai. Ia pernah menimba ilmu kepada Kiai Abdullah di Kradenan Purwodadi, Kiai Asnawi di Kudus, lalu melanjutkan ke pesantren-pesantren di Rembang dan Kajen, Pati.
Salah satu pesan gurunya yang selalu dipegangnya adalah: “Urip kudu ana manfaaté tumrap liyan.” (Hidup harus memberi manfaat bagi sesama.)
Pesan inilah yang kelak menemukan bentuknya dalam dunia kretek. Dari usaha Djambu Bol, Ma’roef membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, sekaligus mengembalikan sebagian hasil usahanya melalui kegiatan sosial. Ia membantu pembangunan Sekolah Al Ma’roef, mendirikan Masjid Al Ma’roef di Pasar Kliwon Kudus, dan sering menolong orang yang datang meminta bantuan.
Dalam hal ini, Ma’roef tidak hanya mencerminkan etika bisnis Islam sebagaimana diajarkan di pesantren, tetapi juga menghidupkan semangat santri entrepreneur yang baru muncul puluhan tahun kemudian. Ia adalah contoh awal bahwa menjadi santri tidak berarti menjauh dari dunia ekonomi, melainkan justru mempraktikkan nilai-nilai religius dalam kemandirian usaha.
Ma’roef lahir dari keluarga santri dan pedagang. Ayahnya, adalah pedagang tembakau dari Loram, Kudus, yang mengambil barang dari Ngadirejo, Temanggung. Dari jalur inilah Ma’roef kelak memiliki jaringan bahan baku kuat untuk mendirikan usaha kretek.
Setelah wafatnya Ma’roef pada tahun 1969, perusahaan dilanjutkan oleh adiknya, Nawawi, seorang mantan laskar Hizbullah semasa revolusi kemerdekaan. Hubungan antara keduanya melambangkan kesinambungan dua wajah santri: yang satu berjuang lewat ekonomi, yang lain lewat perjuangan fisik.
Ma’roef juga dikenal dermawan terhadap saudara-saudaranya. Beberapa adik tirinya ia bantu mendirikan usaha kretek sendiri, seperti Abdul Fatah dengan merek Afa Mari dan Idris dengan merek Bengkoang. Semangatnya bukan hanya tentang bisnis, melainkan tentang keberlanjutan nilai: agar kerja dan kemandirian terus menjadi bagian dari keluarga santri.
Kretek, Santri, dan Diplomasi Budaya yang Menyala
Kisah Ma’roef dan Djambu Bol memperlihatkan bahwa diplomasi budaya tidak hanya lahir dari ruang politik atau meja perundingan, tetapi juga dari ruang produksi—dari tangan-tangan santri yang menggulung, meracik, dan menyalakan api ekonomi lokal.
Kretek menjadi medium perjumpaan antara nilai religius, etika kerja, dan diplomasi budaya. Melalui pengusaha seperti Ma’roef, bangsa ini belajar bahwa menjadi santri bukan berarti menjauh dari dunia nyata, melainkan menghadirkan nilai-nilai pesantren ke dalam denyut ekonomi rakyat.
Kudus, dalam hal ini, menjadi tanah yang unik: di sanalah dua napas besar kebudayaan Indonesia berpadu—santri dan kretek. Dari kota inilah lahir bukan hanya ulama besar, tetapi juga pengusaha dan peracik yang membentuk wajah ekonomi dan budaya bangsa.
Ma’roef dari Djambu Bol adalah contoh santri yang melengkapi dan menghiasi budaya kretek itu sendiri. Ia memperlihatkan bahwa antara santri dan kretek tidak ada jurang pemisah; keduanya justru saling menghidupi.
Dan sebagaimana Kudus Kulon dikenal sebagai tanah para santri dan titik awal industri kretek, di situlah pula lahir kesadaran bahwa doa dan kerja, iman dan keterampilan, spiritualitas dan ekonomi—semuanya menyatu dalam satu aroma yang khas: aroma Kudus.
Kini, jika dunia mengenal Kudus melalui dua hal—santri dan kretek—maka keduanya bukan kebetulan sejarah, melainkan dua sisi dari satu wajah kebudayaan yang sama: wajah Indonesia yang beriman, bekerja, dan tetap berbau cengkih. (*)
Imam Khanafi,
Penulis adalah pegiat literasu dan bergiat di komunitas Cerita Kudus Tuwa (CKT) Kudus, Jawa Tengah.