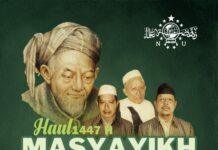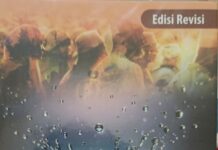Oleh: Sufyan Syafii
“Saya ingin mengoreksi istilah kearifan lokal yang dipakai saat ini, dengan istilah kearifan kebangsaan.”
Demikian Kiai Ahmad Baso dalam webinar yang mengulas mengenai kearifan lokal Nusantara terkait wabah dan pandemi berdasarkan Naskah. Webinar ini digelar setiap Kamis oleh Direktorat Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren (Ditpdpontren) bekerja sama dengan Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), dan belum lama ini dilaksanakan Ma’had Aly Saidusshidiqiyah, Jakarta.
Kiai Ahmad Baso, menjelaskan, bahwa banyak poin terkait hubungan masyarakat Nusantara dengan wabah dan pademi, yang dahulu pernah terjadi beberapa kali. Keahlian Kiai Ahmad Baso terkait penggalian nilai dan kekayaan naskah Nusantara, membuat beberapa poin yang dipaparkan olehnya kiranya menarik untuk diulas lebih lanjut.
Hal ini sangat diperlukan, mengingat era global yang ditandai hilangnya sekat-sekat territorial seperti sekarang ini, di samping memberi kemudahan dalam berinterkasi dan berkomunikasi juga berdampak pada ketahanan integrasi nasional kita.
Diskursus integrasi Nasional kita, berikut wawasan terhadap spirit kebangsaan, tentu lebih menarik jika melibatkan data dan referensi terpadu. Khususnya yang berasal dari data organik asli ‘pribumi’ kita. Jati diri bangsa adalah salah satu identitas penting dalam hal kebangsaan. Ketidakmampuan kita membendung lautan informasi yang tiap sekon, adalah tantangan kita sebagai generasi penerus dalam membahasan makna kebangsaan itu sendiri sesuai zaman.
Sebab diakui atau tidak, masuknya nilai-nilai sosial-budaya melalui media, baik media elektronik maupun media sosial, ikut memberikan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Paling tidak, ada tiga hal penting dalam webinar itu. Pertama, interaksi manusia dengan wabah bukanlah hal baru. Wabah dalam perjalanan sejarah manusia diyakini oleh para peneliti sudah pernah terjadi sejak abad ke-5 Masehi. Penyakit menular dan kematian manusia yang massif banyak dijelaskan oleh relief, naskah klasik, manuskrip di seluruh belahan dunia. Salah satunya di wilayah Nusantara yang pernah terjadi sejak abad ke-15 Masehi.
Wabah penyakit dalam catatan sejarah di Indonesia” oleh arsip penelitian arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis Harriyadi, menyebutkan, jejak wabah di Nusantara pernah terjadi pada 1462 Saka (1540). Ini dibuktikan dari askah lontar yang ditulis dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa Kuno. Naskah itu adalah naskah Calon Arang.
Perlu dipahami, bahwa naskah dan manuskrip sebagai data tertulis yang menceritakan kisah zamannya, adalah data historiografi yang patut dipertimbangkan menjadi sumber penelitian. Sebagai manusia yang tidak mampu kembali pada zaman dahulu, kita perlu melibatkan sumber-sumber penunjang zamannya, untuk dapat menelaah seperti apa kejadian dan kehidupan di zaman dahulu itu. Sebagaimana penelahaan kisah asal mula terjadinya wabah pertama kali di Nusantara yang diceritakan berdasarkan naskah Calon Arang di atas.
Kedua, masyarakat Nusantara sudah memiliki cara tersendiri menghadapi wabah. Kiai Ahmad Baso, menjelaskan, wabah (pageblug) dalam kamus Bausastra Jawa (Poerwadarminta, 1939) diartikan sebagai ungsum lêlara nular (musim penyakit menular). Pagebluk, Jrong dan wabah merupakan sinonim Pageblug.
Jika menelaah lebih lanjut, dalam konteks penelitian sejarah, kerja pekamus bukan hanya menjabarkan definisi, namun juga menyediakan bukti adanya realitas. Pageblug, Jrong, atau Waba merupakan bukti bahwa pernah terjadi pageblug yang melanda masyarakat Jawa. Ini menandakan bahwa peristiwa itu bukan hoaks sejarah.
Kiai Baso juga menambahkan, bahwa sudah sekian kali wabah menyerang wilayah Nusantara. Misalnya pada 1636 terjadi serangan epidemi di Makassar yang berlangsung selama 40 hari dan merenggut 60.000 jiwa. Pada 1625-1630 terjadi wabah yang cukup besar. Dan pada 1626, terjadi wabah besar yang menewaskan 2/3 penduduk Jawa Tengah. Data ini sejalan dengan temuan pihak arkeologi Nasional, yang menyatakan dalam publikasi penelitiannya terkait wabah penyakit dalam catatan sejarah di Indonesia.
Data Kiai Ahmad Baso ini kiranya bisa diperkuat dengan pandangan Anthony Reid dalam bukunya “Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680”. Di mana wabah sangat dimungkinkan sudah terjadi berabad-abad lamanya di Nusantara. Meskipun termasuk wilayah tropis, interaksi matirim internasional yang terjalin dengan belahan dunia lainnya, disinyalir merupakan indikasi kuat terjadinya penyebaran virus.
Meski dalam beberapa kasus, wabah yang terjadi di wilayah Nusantara juga terjadi dengan keadaan kita sendiri, sebagaimana wabah Pes yang pernah menyebabkan ribuan orang meninggal di Malang pada awal 1900-an. Vonis kuat para dokter Belanda saat itu, virus terbawa dari proses haji (pilgrimage), yang terbantah dengan penemuan peneliti lainnya yang menemukan bahwa virus ini rupanya berasal dari impor beras Rangoon, Burma (kini: Myanmar). Ada beras yang diimpor dari Rangoon ke Hindia-Belanda membawa tikus-tikus terjangkit basil Yersinia Pestis.
Ketiga, sikap optimisme masyarakat kita ketika terjadi wabah. Statemen ini bukan tanpa sebab. Dalam Serat Centhini (ed. Kamajaya, jilid 11, hal. 321) misalnya. Petikan yang berbunyi di bawah ini tersirat makna keyakinan dan optimisme.
Nagri nêdhêng lagya rêtu | rusak kambah ing pagêring | papati tanpa pêgatan | sapraptane Darmèngbudi | praja nulya lir tinamban | nulak wawêlaking nagri ||
Katumbal ing jalma luhung | gring sore esuk basuki | gring sore esok waluya | | samya suka tyasing janmi | yèku margane prajarja | olya amupangati ||
Terjemah; Saat itu negeri sedang ditimpa wabah yang merusak. Banyak orang terpapar, hingga meninggal, tiada henti. Seorang waliyullah tiba, berkeliling negeri.
Mengerahkan segenap tenaga untuk menolak bala’ dari seluruh negeri yang banyak merenggut nyawa manusia. Akhirnya, mereka yang sakit di waktu pagi, pada sore harinya mulai pulih, yang di waktu sore esok sakit, paginya sudah sembuh.
Petikan Serat ini secara implisit menceritakan sebuah proses terjadinya wabah yang terjadi di suatu Negeri (Palembang). Dalam negeri itu, seorang Olya / Aulia Bernama bernama Ki Darmengbudi (guru Syekh Amongrogo) yang melakukan segenap usaha untuk mengusir wabah itu. Singkat kisah, masyarakat yang tatkal aitu banyak yang meninggal tiba-tiba kemudian Kembali hidup normal (gring sore esuk basuki | gring sore esok waluya | | samya suka tyasing janmi | yèku margane prajarja).
Petikan ini mengajarkan kepada kita, bahwa tokoh agama perlu dililbatkan dalam penanganan wabah, semata agar umat tidak resah dan kehilangan arah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu optimis, bahwa segala wabah sebagai bagian dalam sejarah dunia pasti akan pergi. Selama kita meyakini bahwa praja nulya lir tinamban | nulak wawêlaking nagri, Ketika semua usaha sudah dilakukan oleh banyak pihak dan segenap kekuatan sudah dikerahkan, tugas kita sebagai masyarakat adalah patuh dan mengikuti arahan dari tokoh agama (dan juga pemerintah terkait).
Tiga poin di atas, tentu merupakan nilai baik yang perlu dipertahankan. Bahwa semua yang terjadi sudah digariskan Tuhan, dan kita sebagai manusia haruslah terus berprasangka baik bahwa segala ketetapan-Nya adalah qadla dan qadar yang menyisakan makna dan hikmah yang pasti indah di masa berikutnya. (*)
Sufyan Syafii,
Penulis adalah Penggiat dan penikmat Sejarah. Pengajar Sejarah di Mahad Aly Saidusshiddiqiyah Jakarta. Bidang Litbang Matan DKI Jakarta.